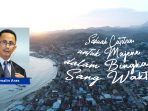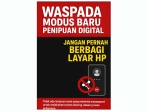Majene mengalami “kemunduran pertama” dalam sejarah pemerintahan pada 1959, ketika Daerah Mandar dibubarkan lalu dilebur menjadi Daerah Tingkat II Status Majene sama dengan Mamuju dan Polewali di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada saat itu, Baharuddin Lopa diangkat menjadi Bupati Majene, Hasan Mangga menjadi Bupati Polmas, dan Andi Paccoba sebagai Bupati Mamuju. Dan, ketika Sulawesi Tenggara terpisah dari Sulawesi Selatan tahun 1964, tiga daerah Mandar tetap menjadi kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.
Empat puluh tahun kemudian, status administratif bekas wilayah Mandar berubah, setelah dimekarkan dari provinsi induknya menjadi provinsi baru dengan nama Sulawesi Barat. Wilayahnya mencakup seluruh Mandar. Namun ibukotanya bukan lagi di Majene, melainkan di Mamuju. Perubahan ini menandai “kemunduran kedua” Majene dalam sejarah pemerintahan di bekas Mandar.
Kalau sudah begini, apa yang dapat dibangggakan oleh penduduk di bekas ibukota Mandar ini? Apakah akan dibuat menjadi Kotamadya Mandar sebagai “prasasti” ibukota Mandar, ataukah menjadi Kota/Kotamadya Majene? Apa pun atributnya, kita perlu sebuah kotamadya atau kota di Provinsi Sulawesi Barat, seperti provinsi lain di Tanah Air.
Sebelum mewujudkan ide tersebut, izinkan saya mengajak hadirian semua membaca sejarah Majene dalam arus perjuangan bangsa. Saya mulai dengan kisah perlawanan I Calo Ammana I Wewang, kemudian perjuangan GAPRI 5.3.1 dan akhirnya ALRI-PS Mandar. Dari sana lahir tokoh-tokoh yang layak dijadikan Pahlawan Daerah dan/atau Pahlawan Nasional.
1. Perlawanan I Calo Ammana I Wewang
Pada 9 Juni 1905, Maradia Pamboang, I Lata (1892-1907) dan Maradia Banggae, I Juwara (1892-1907) menandatangani kontrak politik di Makassar mengenai pelimpahan pajak tol dan perkapalan kepada Belanda sebanyak 3.000 gulden per tahun. Jadi, semua pendapatan cukai tol dan perkapalan di Pamboang dan Majene harus disetor kepada Belanda di Majene. Kewajiban ini juga berlaku kepada Balanipa, Sendana, dan Binuang.
Berlatar monopoli pelabuhan tersebut, Ammana I Wewang bersama 150 orang penduduk merebut kota pelabuhan Majene pada 6-7 Juni 1906. Mereka membakar pesanggrahan dan rumah syahbandar. Seorang pegawai kontrolir Belanda, Schmidhamer, digiring ke pedalaman kemudian dibunuh. Sementara kontrolir Ketting Olivier berhasil menyelamatkan diri ke Parepare dengan sebuah lepa-lepa.
Setelah kejadian itu, Asisten Residen Mandar Vermeulen meminta bantuan dari Makassar. Pada 13 Juni, kapal api Siboga membawa 60 pasukan dipimpin Kapten Lenshoek tiba di pantai Mandar. Mereka menyerang pusat pertahanan Ammana I Wewang di pedalaman Balanipa, Allu. Terjadi kontak senjata antara kedua pihak pada 22 Juni. Maradia Allu, I Kaco Ammana Pattolawali, bersama Maradia Pamboang dan Maradia Banggae menyelamatkan diri ke pedalaman Pamboang. Dua penguasa terakhir kemudian menyerah kepada Belanda pada Juli 1907. Dua bulan kemudian, Amanna I Wewang ditangkap dan diasingkan ke Tanjung Pandan Belitung selama 36 tahun (1908-1944). Pada akhir masa Jepang, ia kembali ke Majene dengan perahu lete mendarat di pantai Bababulo.
Pelajaran dari peristiwa ini adalah bahwa pelabuhan merupakan simpul utama sejarah Mandar. Untuk menguasai Mandar, maka yang harus dikuasai adalah pelabuhan, karena ia merupakan pusat ekonomi maritim. Itulah sebabnya Belanda berupaya menguasai pelabuhan-pelabuhan di Mandar yang menulut api perlawanan rakyat di bawah pimpinan Ammana I Wewang.
2. Perjuangan GAPRI 5.3.1
Kelaskaran Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia 531 (GAPRI 531) dibentuk pada 2 November 1945. Tokoh utamanya ialah seorang guru, Kepala SR Bababulo I yakni Siti Maemunah dan suaminya, Muhammad Djud Pantje, yang juga Kepala SR II Ba’babulo. Rumah mereka di Baruga menjadi markas utama GAPRI 531 dengan wilayah operasi mencakup seluruh Mandar.
Organisasi ini bernafaskan Islam. Setiap angka di belakang kata GAPRI punya makna. Angka 5 sebagai ikatan, bahwa selama berjuang tidak boleh melalaikan shalat 5 waktu. Angka 3 bermakna 3 jenis pengorbanan yaitu pikiran, tenaga, dan harta. Angka 1 adalah tujuan perjuangan, yakni mencapai Indonesia Merdeka yang berdaulat 100% dengan ridha Allah SWT. Dengan demikian, GAPRI 5.3.1 menggambarkan persatuan dari semua pejuang merah putih yang bergerak serentak dengan keikhlasan dan pengorbanan karena Allah demi Nusa dan Bangsa.
Sepanjang tahun 1946, GAPRI melakukan berbagai aksi terhadap NICA dan KNIL. Bulan April menyerang tentara KNIL di Segeri, Pangale, dan Pamboang. Tiga bulan berikutnya menyerang markas KNIL di Tonyamang (Polawali). Pada Agustus dan September, GAPRI menyerang tentara KNIL di Pussana dan Buttu Segeri. Pada Desember mereka menyerang tentara Belanda di Kota Majene dan Pamboang. Semua aksinya dilakukan secara sporadik, serentak, dan kadang-kadang spontan yang sangat merepotkan musuh.
Untuk melemahkan perjuangan rakyat, Belanda menangkap para pemimpin dan pasukan GAPRI. Pada 4 Februari 1947, polisi menahan Siti Maemunah. Tiga hari kemudian Djud Pantje juga ditangkap. Para pimpinan pejuang, seperti Kanjuha dan Sulemana yang berkeliaran di pegunungan Adolang, Segeri, Pu’awang, dan Palarangan ditangkap saat memasuki kampung mencari kebutuhan logistik.