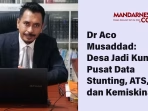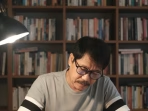(Memahami Mandar dari Keterbatasan Pengetahuan)
Oleh : Muliadi Saleh
Di barat Sulawesi, tempat matahari tenggelam dengan lembut di pelukan laut, bermukim sebuah suku yang menyatu dengan gelombang, menari bersama angin, dan berakar di tanah yang subur penuh makna. Ia dikenal sebagai Mandar—lebih dari sekadar nama suku, ia adalah denyut nadi sebuah peradaban maritim yang menjahit laut dan darat menjadi satu kesatuan yang harmoni.
Orang Mandar lahir dari pelukan samudra, besar dalam semilir angin pesisir, dan dewasa di bawah lindungan tradisi yang kuat. Di pagi yang tenang, ketika langit masih menyimpan sisa bintang, perahu sandeq meluncur ke cakrawala. Perahu ramping bersayap segitiga itu bukan cuma kendaraan, tapi lambang hidup: kecepatan, keberanian, dan keluwesan. Pelaut Mandar bukan hanya menaklukkan gelombang, mereka berdialog dengan laut, membaca diamnya dan merasakan riaknya.
Kekuatan Mandar tidak hanya terletak di laut yang biru. Di ruang-ruang rumah panggung, di antara kayu tua yang harum oleh waktu, para perempuan Mandar menenun dengan tangan yang sabar dan jiwa yang hening. Di situlah lipa saqbe—kain sutra khas Mandar—lahir. Ia bukan hanya tenunan benang, tetapi tenunan makna. Dalam setiap helainya, tersimpan pelajaran tentang kesabaran, sebab sehelai takkan terbentuk tanpa ketekunan waktu. Ia mengajarkan kesadaran, bahwa setiap motif adalah hasil perenungan dan keterhubungan dengan alam. Tenunan ini juga menjunjung tinggi etika dan estetika—bahwa keindahan bukan hanya soal rupa, tapi juga soal sikap. Menenun lipa saqbe adalah menenun hidup itu sendiri: penuh pengulangan, kesalahan kecil yang disulam menjadi sempurna, dan harmoni yang muncul dari ketekunan.
Perempuan penenun bukan hanya pelestari budaya, tetapi juga penjaga nilai. Mereka adalah guru tanpa kelas, yang mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa untuk menjadi indah, hidup harus dijalani dengan tenang, sabar, dan tulus. Setiap motif, warna, dan pola pada lipa saqbe bukan hanya warisan, tapi doa yang dirajut dalam keheningan.
Dan di antara laut dan tenunan, di dapur yang hangat oleh bara dan aroma, orang Mandar mengekspresikan cinta mereka kepada kehidupan lewat masakan. Jepa—’pizza’ ala Mandar berbahan singkong yang dipanggang dengan sabar di atas api kecil—menjadi simbol daratan: hasil kerja keras petani, kekuatan akar. Ia kerap berpadu dengan bau piapi, olahan ikan laut yang dimasak dalam kuah yang sarat bumbu khas, kadang dengan ‘kaloe’ (asam mangga), irisan ‘lasuna’ (bawang), dengan tumpahan minyak Mandar yang wangi . Inilah pertemuan antara laut dan darat dalam bentuk yang paling sederhana dan jujur. Tak ada yang lebih Mandar daripada perpaduan ini: jepa yang kering dan hangat, bersanding mesra dengan bau piapi yang gurih dan segar..
Masyarakat Mandar memegang teguh nilai sipamandaq, semangat kolektif untuk saling menjaga, menopang, dan berbagi. Dalam suka dan duka, mereka hadir sebagai satu tubuh. Rumah-rumah terbuka, pintu-pintu tidak dikunci, dan anak-anak tumbuh di bawah pengawasan semua mata yang penuh cinta. Ketika satu orang berbahagia, satu kampung ikut menari. Ketika satu keluarga berduka, yang lain datang membawa peluk dan pelipur.
Lihatlah, bagaimana anak-anak lelaki Mandar yang baru dikhitan dijunjung tinggi dalam tradisi sayyang pattu’du. Di atas kuda yang dihias megah, mereka diarak mengelilingi kampung, ditemani rebana dan syair-syair zikir. Ini bukan sekadar perayaan, tapi pelajaran: bahwa menjadi dewasa adalah kehormatan, dan adat adalah cahaya yang membimbing langkah.
Bahasa Mandar pun turut menjaga keberlangsungan jiwa budaya ini. Dalam logatnya yang khas dan ritmenya yang syahdu, tersimpan kosakata tentang laut, cinta, doa, dan keseharian. Bahasa ini adalah tempat tinggal terakhir dari kearifan lokal—tempat kata bukan hanya bunyi, tapi juga makna dan sejarah.
Dibalut dalam busana adat seperti baju ‘pokko’ bagi perempuan dan songkok recca bagi pria, orang Mandar tampil dalam keelokan yang tak sekadar indah, tapi bermartabat. Setiap helai kain, setiap sulaman, dan setiap warna menyuarakan keanggunan yang diwariskan, bukan dipaksakan.
Maka ketika membicarakan Indonesia sebagai negeri maritim, jangan lupa menyebut Mandar—sang penjaga gelombang, pemeluk tradisi, dan pengembara yang tak gentar menantang cakrawala. Dari Paku ke Suremana, Panti Polewali hingga Pamboang, dari Pitu Ulunna Salu ke Pitu Baqbana Binanga, suara Mandar terus bergaung. Tidak hanya dalam lagu-lagu tua yang dinyanyikan nelayan, tapi juga dalam semangat hidup.