Proklamasi sebatas tanggal 17 Agustus, selebihnya adalah menyiasati kehidupannya dengan tetap maksyuk dalam buaian tirani untuk membunuh saudaranya yang tak lagi dibutuhkan dalam menopang kehidupannya.
Para pejuang Rakyat Indonesia (baca: Mandar) hanya sampai di gerbang kemerdekaannya, sementara kemerdekaan itu masih disekap dalam kantong-kantong para pecundang yang jadi budak Pemerintah Hindia Belanda. Para pejuang itu mati kelaparan tak dapat makan, sementara para pecundang itu makan enak tanpa berjuang.
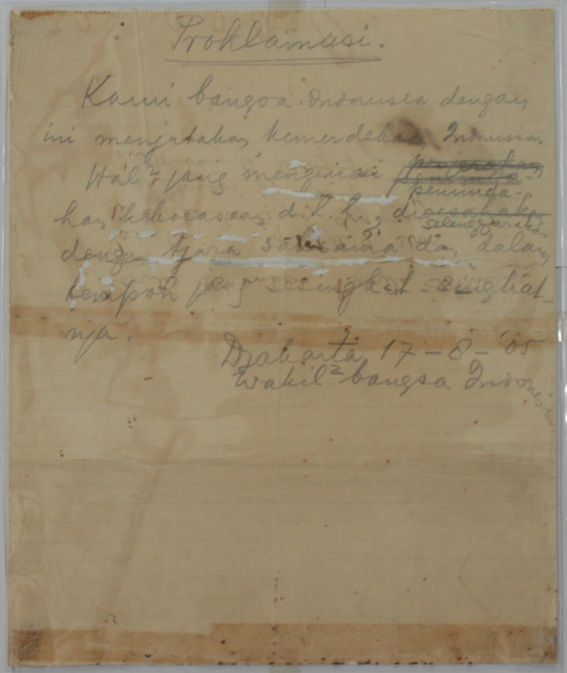
Sepanjang tahun 1945-1950, tak terhitung lagi berapa nyawa para pejuang yang meregang nyawa, berapa rakyat yang mati kelaparan, berapa ribu pejuang yang tergelepar dihantam popor sejata laras panjang dan siapa-siapa saja yang menikimati pengorbanan rakyat itu untuk tetap bisa hidup terhormat dan kaya raya.
Tahun 1950, para pejuang yang tersisa berharap pada Negara agar nasibnya bisa berubah saat penyerahan kedaulatan. Lagi-lagi mereka dihadapkan pada lembaran-lembaran resmi Negara yang mengharuskan mereka mengisinya sendiri.
Bagaimana mungkin mereka bisa mengisi kolom pada lembaran Negara itu ditengah kondisi tak bisa baca tulis?. Bagimana mereka diharapkan bisa baca tulis sementara kebijakan pendidikan penjajah tak memihak kepada rakyat kecil. Pendidikan pada masa penjajahan hanya mereka yang berdarah biru atau yang orang tuanya abdi Belanda. Andai diberi kesempatan untuk belajar, bagaimana mungkin bisa sekolah ditengah situasi ekonomi yang terpuruk. Jangankan sekolah untuk makan saja susah.
Lembaran tanggal di tahun 1950-an itu nyaris menjadi tamparan yang serasa popor bedil menghantam mereka. Nasib manusia Mandar yang bergelar pejuang itu akhirnya hidup tersisih dan terpaut jauh dari spasi bangsa besar ini. Mereka tak lagi bisa berharap pada Negara, sebab Negara saat itu hanya bagi yang bisa baca tulis.
Mereka yang tak bisa baca tulis menjadi terlantar dan diperdaya menjadi pasukan cadangan dan hidup di hutan. Mereka menjalani hari-harinya di hutan dengan harapan bisa hidup layak. Mereka tak pernah membayangkan bahwa kehidupannya di hutan kelak akan menjadi bagian dari sebuah konspirasi politik dari para elit yang birahi kuasanya sedang kilmaks.
Hidup di hutan-hutan Sulawesi yang masih perawan rupanya membawanya ke dalam kehidupan yang rawan. Para pejuang kemerdekaan itu harus menerima status baru sebagai pemberontak sebab upaya yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar tak juga mampu mengubah semua keputusan Kawilarang.
KGGS (Kesatuan Gerilja Sulawesi Selatan) yang mewadahi mereka sejak masa revolusi fisik melawan Belanda tak juga bisa menampung semua harapan mereka. Pasca kemerdekaan, pasukan gerilya ini statusnya semakin tidak jelas.
Kebijakan pemerintah pusat sebatas menampung pasukan gerilya semacam ini di seluruh wilayah Indonesia dengan membentuk Corps Tjadangan Nasional (CTN). Presiden Sukarno selanjutnya menugaskan putra asal Sulawesi Selatan, Letkol (Overste) Kahar Muzakkar untuk menangani KGSS agar ditampung dalam CTN.














