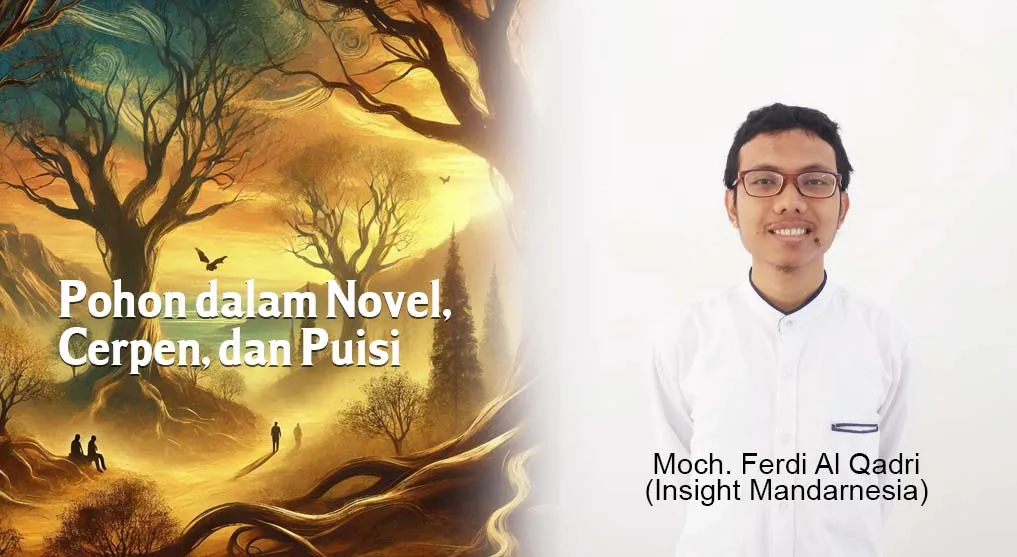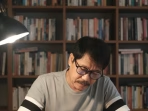Oleh Moch. Ferdi Al Qadri (Insight Mandarnesia)
Prabowo Subianto berpidato pada Senin terakhir 2024. Orang-orang yang tak hadir di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta Pusat, ramai memberi tanggapan.
Presiden mengingatkan kalau sawit juga pohon: punya daun yang dapat menyerap CO2. Penyamaan ini mirip dengan kesimpulan keempat dalam naskah akademik “Kelapa Sawit sebagai Tanaman Hutan Terdegradasi” susunan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO): “Tanaman kelapa sawit memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi dan paling efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari dibandingkan dengan tanaman komoditas kehutanan lainnya.”
Naskah akademik itu beraroma pamrih politik-bisnis. Dalih peningkatan ekonomi tak dapat dibenarkan bila memicu kerusakan ekosistem dan membuat masyarakat adat tercerabut dari ruang hidup mereka yang berbasis alam (Koran TEMPO, 7 Januari 2025).
Pernyataan Presiden ingin “tambah tanam sawit” juga direspon Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dalam situs resminya, WALHI mengunggah Siaran Pers pada Rabu, 1 Januari 2025: “Perluasan ekspansi perkebunan sawit skala besar akan semakin memperpanjang rantai konflik agraria, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, bencana ekologis, dan korupsi di sektor sawit.”
Agar tak hanyut arus deras perdebatan, kita mendingan mampir ke pohon yang “ditanam” sastrawan. Nur St Iskandar mengarang Kenangan Masa Kecil. Balai Pustaka menerbitkan novel itu sebagai cetakan kelima pada 1983. Di situ ada pohon jeruk.
Terkisah rumah Manun dikelilingi pohon buah-buahan. Anak-anak lewat di bawahnya sering menengadah demi melihat buah sudah ranum. Kejadian berikutnya mungkin dua: “Kalau ada yang jatuh, diambil oleh mereka itu. Dan tidak jatuh dilemparinya dengan batu.”
Sebagai bocah pemilik pohon, Manun tak lekas mengusir dengan tongkat di tangan. Ia tahu akibat bila berbuat demikian: “mereka itu datang pula dengan lebih ganas!” Yang menentukan tindakannya ialah nasihat ibunya: “Tidak ada yang lebih baik daripada dengan lemah lembut saja.” Ibu sengaja tak sampai solusi. Manun harus memikirkan sendiri, dalam kapasitasnya sebagai anak-anak pula, apa yang harus diperbuat.
Hari berikutnya, Manun justru memanggil para calon “pemungut” atau “pelempar” ketika hendak lewat. Ia melakukan sesuatu yang tak disangka: “saya berikan kepada mereka itu jeruk sebuah seorang.” Mereka keheranan, air mukanya kemerah-merahan tanda malu. Setelah berterima kasih dan beranjak pergi, muka mereka berubah berseri-seri dan bersaing jeruk siapa yang paling enak.
Pemberian itu membuahkan hasil: “Mereka itu tidak datang meminta-minta, jangan mencuri! Bahkan tidak pernah lagi mereka itu melihat ke atas, jika mereka itu lalu di bawah pohon-pohon itu.” Kita membaca sifat pekerti manusia timbul karena perbuatan baik, bukan sebaliknya.
Pada masa dan tempat berbeda, kita mengikuti pengalaman seorang lelaki tua dan pohon nangka. Kita membacanya dalam Sebatang Kayu untuk Tuhan. Kuntowijoyo dalam karangannya itu menggugat pemahaman kita mengenai keikhlasan.
Sebuah surau sedang didirikan. Lelaki sudah tua ingin membantu walau sedikit. Dilihatnya satu pohon nangka telah mati di kebunnya. Batangnya tinggi, besar, dan kokoh. Ia sendiri yang menanam, memelihara, dan menikmati hasilnya selama bertahun-tahun.
Lelaki tua sadar akan masuk dalam tanah. Tubuhnya bakal hancur dalam kubur. Hidupnya jangan tersia-siakan. Kuntowijoyo menulis batin lelaki tua: “Ia akan membuktikan dengan benda yang nyata, sekali dalam hidupnya dapat juga ia menyumbang untuk Tuhan.” Dibayangkannya batang kayu dari pohon nangka jadi saksi atas dirinya kelak.
Mata tua melihat pohon nangka dan tak ada lain dalam benaknya selain Tuhan. Orang sekampung tak akan tahu kalau sebatang batang kayu yang “terdampar” di surau adalah pemberiannya. Mereka akan diliputi tanda tanya, sedang Tuhan dan malaikat-Nya saja yang tahu jawabannya. Lelaki tua tersenyum bahagia.
Sebatang kayu tak melulu jadi balok dan papan untuk dijual. Pun terlibat dalam pembangunan rumah ibadah tak mesti menyumbang uang. Mendapat banyak uang membikin kaya, memberikannya banyak-banyak pertanda kekayaan. Manusia mungkin berbangga atas pencapaian itu. Namun, Kuntowijoyo memberi pilihan: “Kebanggaan yang terpendam lebih baik dari kebanggaan yang terbuka. Kebanggaan yang terpendam membuat orang tertawa. Dan senyum lebih abadi dari tertawa.”
Pohon lain dikisahkan dalam puisi. Dalam Makrifat Daun Daun Makrifat, Kuntowijoyo menyebut pohon cemara: Di antara nama-nama indah/ aku pilih Al-Hayyu/ yang mengalirkan oksigen ke ujung pohon/ dan menggoda kerisik cemara.
Kehadiran pohon cemara, sebagai pengejawantahan Al-Hayyu, memastikan oksigen tetap mengalir dalam darah manusia. Ada di halaman depan rumah. Banyak di dalam hutan. Berjejer rapi di kebun-kebun wisata alam. Manusia masih akan hidup seribu tahun lagi selama ada pohon cemara. Tuhan “maha hidup” dalam pohon cemara.
Masih dalam Makrifat Daun Daun Makrifat, pohon tanpa nama hadir di tengah manusia dan Tuhan: Dengan ikhlas/ kutanam pohon untuk burung/ yang sanggup/ memuji Tuhan dengan sempurna. Kuntowijoyo meyakini keampuhan burung-burung dalam memuji Tuhan. Sedang kita manusia acap kali memanggil-Nya untuk diberi perintah-perintah: lancarkan bisnisku, naikkan jabatanku, banyakkan keturunanku.
Bila manusia menebang semua pohon, menggantinya dengan tambang dan gedung-gedung, kepada “siapa” lagi kita menitipkan salam kepada Tuhan?
Kita rehat sejenak dari berita-berita, pernyataan-pernyataan, dan kebijakan-kebijakan mementingkan pohon sawit. Dengan membaca prosa dan puisi, kita menanam, merawat, dan melestarikan harapan baik atas nasib pohon-pohon di hutan abad XXI.